Dalam
penggalan sejarah Rasulullah SAW kita kenal satu masa yang disebut dengan “amul
huzni” (tahun berduka cita). Yaitu ketika dua orang yang sangat beliau cintai
sekaligus sangat berjasa dalam perjalanan kehidupan (baca: dakwah) beliau
meninggalkan beliau untuk selamanya dalam waktu yang relatif bersamaan. Dua
orang itu adalah, istri beliau tercinta, Siti Khadijah ra, dan paman beliau Abu
Thalib.
Sebagi manusia
normal, ada gurat duka di wajah Rasulullah saw, ketika ditinggal pergi istri
tercinta. Sungguh, penggalan indah dan penuh makna dari setiap detik kehidupan
beliau dengan Siti Kahdijah ra tak kan pernah bisa tergantikan oleh istri-istri
beliau yang lain.
Seperti kita
tahu, Khadijah adalah istri yang begitu beliau sayangi yang selama ini telah
menopang perjuangan kehidupan beliau, baik secara psikologis maupun ekonomis.
Tak hanya itu, Khadijah juga tercatat sebagai orang pertama yang mengimani
dakwah yang dibawa Rasulullah SAW. Tanpa ragu Khadijah membenarkan misi
kenabian yang beliau emban sebelum ada orang lain yang meyakininya. Betapa
besarnya cinta beliau kepada Khadijah bisa kita rasakan ketika beliau pernah
mengungkapkan, “ Sungguh, Khadijah adalah anugrah Allah terbesar kepadaku. Dia
mengimani ku saat orang lain mengingkariku, dan dia melindungiku saat orang
lain memusuhiku”.
Tak lama waktu
berselang, goresan kesedihan itu beliau rasakan semakin dalam, tatkala paman
yang beliau hormati, Abu Thalib, juga kembali pada Allah SWT untuk selamanya.
Meskipun sampai akhir hayatnya, Abu Thalib tak pernah mau bersyahadat untuk
memeluk Islam, dari sejarah kita tahu bahwa beliau tidak hanya telah berjasa
dalam mengasuh beliau semenjak ibunya Aminah meninggal, tapi juga telah menjadi
tameng hidup kelancaran dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW dari rongrongan
kaum kafir Qurais.
Abu Thalib
pergi di saat kuncup dakwah yang beliau semai belum begitu mekar. Paman yang
beliau hormati itu meninggal saat beliau masih sangat membutuhkan sosok yang
begitu tegar dan berani berdiri di shaf depan melindungi diri beliau dari
kejaran kafir Quraisy yang sekaligus juga bisa diartikan untuk memagari proses
dakwah yang sedang beliau lakukan.
Demi mengobati
luka duka itu, beliau memutuskan untuk hijrah ke Tha’if. Beliau pergi dengan
membawa segumpal harap, penduduk Tha’if akan menerima beliau dengan hangat dan
terbuka. Namun sesampai di Tha’if, harapan tersebut hilang bagai embun yang
disapu sinar mentari. Bukan sapa hangat yang beliau terima, tapi cemooh dan
lemparan batu yang didapat. Dalam sejarah disebutkan bahwa lemparan batu itu
sampai membuat satu gigi Rasulullah SAW patah. Masyarakat Tha’if mengusir
Rasulullah keluar dari kota. Kejadian ini tentu menambah goresan luka itu
semakin dalam.
Menerima
perlakuan kasar, dalam kesedihan yang mendalam, marahkah beliau? Putus asakah
beliau? Apakah beliau kemudian merencanakan aksi balas dendam? TIDAK, dengan
sabar beliau malah mendoakan : “Allahummahdi qaumi fainnahum la ya’alamuun”.
(Ya Allah, berilah kaumku hidayah, karena sesungguhnya mereka belum
mengetahui).
Kemudian
sejarah menceritakan sepuluh tahun kemudian, dengan berbondong-bondong
masarakat Tha’if masuk Islam. Bahkan pada zaman khalifah Abu Bakar, disaat
beberapa golongan tidak mau membayar zakat, masyarakat Thai’if lah yang
bersegera menunaikan pembayaran zakat.
Rasulullah
yang mulia, melalui sepenggal sirahnya, mengajarkan kepada kita tentang satu
mentalitas atau karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim yang
beriman, yaitu satu nilai yang kita sebut dengan optimisme. Secara sederhana
optimisme bisa kita pahami sebagai sikap mental yang selalu penuh harap dan
keyakinan tentang masa depan yang lebih baik.
Potret
optimisme Rasullulah SAW ketika menghadapi penolakan masyarakat Tha’if, tergambar
jelas dalam untaian doa yang beliau lantunkan. Rasulullah mengajarkan, sesulit
dan seberat apapun kondisi yang kita hadapi, harus tetap ada optimisme, karena
optimisme bagi seorang muslim merupakan manifestasi keyakinan akan keberadaan
dan pertolongan Allah SWT.
Optimisme
seorang muslim bukanlah optimisme yang didirikan diatas tanah kosong, tapi
optimisme tersebut didirikan di atas kekokohan iman kepada Allah SWT. Dengan
kata lain, sikap mental yang selalu optimis dengan masa depan yang lebih itu
adalah konsekwensi logis dari keimanan dan keistqamahan kita dalam mengamalkan
ajaran dinul Islam ini.
Sebagaimana
Allah berfirman, “ Sesungguhnyaorang-orang yang berkata bahwa tuhan kami adalah
Allah dan mereka istqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka (dan
berkata), “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati; dan
bergembiralah kamu (memperoleh) sorga yang telah dijanjikan kepadamu”.
(Fusshilat:30).
Kalau kita
melihat berbagai kenyataan yang ada di depan mata kita hari ini, maka kita akan
menemukan bahwa ada begitu banyak masalah yang bisa saja membuat kita begitu
tertekan. Beragam permasalahan hidup itu bisa kita rasakan baik dalam lingkar
kita sebagai individu, sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari anak
bangsa, maupun permaslahan kita sebagai satu ummah.
Di level
individu, sangat mungkin ada diantara kita yang senantiasa bergulat dengan
permasalahan pribadinya setiap harinya. Masalah itu bisa terkait dengan masalah
keluarga, hubungan dengan anak dan istri yang tidak harmonis, sakit yang tak
kunjung sehat, susahnya mencari pekerjaan, studi yang tak juga selesai,
atau masalah doa dan impian yang tak kunjung terwujud.
Semua problema
itu sangat mungkin menjebak kita untuk berkeluh kesah dan bahkan mungkin sampai
pada situasi dimana kita merasa hopeless, putus asa, dan frustasi. Bahkan bisa
sampai pada titik ekstrim, yaitu ketika kita mulai mempertanyakan pertolongan
dan keadilan Allah. Nauzubillahi min zalik.
Pada tataran
masyarakat, saat ini kita juga harus berhadapan dengan seabrek problema sosial
yang semakin hari justru makin mengkhawatirkan. Semakin meningkatnya tindak
kejahatan dalam berbagai bentuk dalam masyarakat kita, misalnya, kadang membuat
kita cendrung “kehilangan akal” untuk menghadapinya. Atau ketika aktifitas
dakwah cukup marak hadir di tengah masyarakat kita hari ini, pada saat yang
sama fenomena maksiatpun juga merajalela dalam berbagai bentuk dan modus
operandi yang “lebih canggih”.
Apalagi kalau
kita melihat diri kita dalam lingkaran yang lebih luas, sebagai bagian dari
anak bangsa yang bernama Indonesia. Sungguh, cerita keseharian kita sebagai
bangsa dipenuhi oleh cerita-cerita sedih dan paradoks. Sebuah realitas
yang membuat potret negeri dengan komunitas muslim terbesar di dunia ini
semakin buram.
Kisah kita
sebagai bangsa sampai hari ini masih berkisar tentang tingginya angka
kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, buruknya pelayanan birokrasi,
rusaknya mentalitas sebagian anak bangsa, dan (masih) maraknya prilaku korupsi.
Tak sampai di sini, musibah dalam bentuk bencana alampun datang silih berganti.
Belum sembuh luka saudara-saudara kita di Aceh pasca Tsunami, berturut-turut
belahan negeri Indonesia yang lain seperti Jogya, Pengandaran, dan Sidoardjo
juga harus merasakan pedihnya luka ini. Maka, sepertinya lengkap sudah “derita”
kita sebagai anak bangsa yang bernama Indonesia.
Sampai di
sini, pertanyaan kita adalah Kapan semua cerita sedih ini akan berakhir, atau
masih adakah harapan tentang masa depan yang lebih baik itu?
Kalau kita
telusuri kisah orang-orang yang tersesat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh
diri, maka kita akan temukan salah satu peyebabanya adalah ketika yang
bersangkutan telah kehilangan harapan tentang jalan keluar dari permasalahan
yang dia hadapi. Orang yang kehilangan harapan, sesungguhnya yang bersangkutan
telah kehilangan hidup itu sendiri. Karena harapan adalah sumber energi
kehidupan. Harapan berfungsi layaknya bensin sebagai sumber energi yang bisa
membuat mobil bisa berjalan. Mobil secantik apapun tak akan berarti apa-apa
tanpa bensin.
Maka menjawab
pertanyaan diatas, sebagai muslim yang beriman tentu seharusnya jawaban kita
adalah bahwa kita tidak boleh berhenti berharap. Kita tidak boleh berputus asa
dengan rahmat Allah. Kita harus yakin dengan janji Allah SWT yang menegaskan
bahwa Dia akan memberikan pertolongan (40:51), penjagaan (10:98), perlindungan,
2:257), jalan keluar dari segenap permaslahan (65:2) dan juga rezki (35:3)
kepada hamba-Nya yang senantiasa beriman dan bertaqwa kepada-Nya.
Dengan
demikian, kalau kita masih menemukan diri kita, baik dalam skala personal
maupun sebagai bagian dari satu ummah yang besar, masih berkutat dengan
berbagai permasalahan yang pelik, mengacu kembali pada firman Allah dalam surat
Fusshilat ayat 30 di atas, yang harus kita interospeksi adalah sampai dimana
kadar keistiqmahan kita sebagai seorang yang telah meyakini Allah sebagai Rabb
kita. Sebagi seorang yang telah memilih Islam sebagai way of life kita.
Istiqamah yang
dimaksud di sini tentu saja dia tidak hanya berarti mengerjakan ibadah mahdah
(seperti shalat, puasa, dll) secara konsisten, namun dia harus dipahami dalam
konteks yang lebih luas bagaimana kita sebagai muslim konsisten menjalankan
semua aspek dinnul Islam yang kaffah itu dalam semua aspek kehidupan kita. Istiqamah
di sini juga berarti bagaimana kita secara terus menerus mengembalikan semua
permasalahan kita tersebut kepada (tuntunan) Allah dan Rasulnya secara
proporsional.
Terkait
masalahan kemiskinan, misalnya, apakah kita sudah menjalankan perintah Allah
tentang berusaha mencari karunia Allah secara maksimal, atau yang terjadi
justru sebaliknya, kita cendrung menjadi orang yang malas dan menghabiskan
sebagian waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal Allah sudah
janji bahwa Allah akan menjamin rezki semua makhluknya (17:31) . Tapi rezki itu
tak kan pernah turun dengan sendirinya bagaikan turunnya embun di pagi hari.
Dia haru dicari dan dijemput dalam bentuk usaha yang sungguh-sungguh.
Bagi kita yang
sudah berkecukupan, sudahkah kita, selain menjadi seorang muslim yang sholeh
secara pribadi, juga sholeh secara social. Apakah ada setitik kesedihan dan
empati di hati kita saat kita makan dengan lahap, sementara ada begitu banyak
saudara-saudara kita yang lain selalu hidup dalam berkekurangan. Sudahkah kita
khawatir digolongkan Allah ke dalam golongan yang mendustakan agama (107:1-3),
lantaran kita membiarkan kemiskinan di hadapan kita. Pendeknya, apa yang telah
kita lakukan dalam rangka memerangi kemiskinan ini sebagi bentuk istiqamah kita
menjalankan ajaran dinnul Islam, yang tidak hanya mengajarkan kita sholeh
secara pribadi tapi juga secara social?
Sungguh,
tulisan yang pendek tak cukup untuk mengurai secara detail beragam permasalahan
yang kita hadapi. Poin penting yang saya ingin tegaskan adalah bahwa kalau kita
konsisten mempraktekkan ajaran Islam ini secara kaffah dalam setiap gerak
kehidupan kita, maka InsyaAllah memang kita tidak perlu bersedih dengan setiap
problema kehidupan ini. Kita tak kan pernah kehilangan harapan tentang masa
depan yang lebih baik itu. Kita akan selalu optimis dengan segenap pertolongan
Allah, karena memang Allah tak kan pernah mengingkari janji-Nya. Marilah
belajar kepada tetes-tetes air yang mampu melubangi batu karang yang keras,
hanya kerena air yang sesungguhnya lembut itu menjalankan sunnatullah, secara
konsisten, tanpa henti menetes dan menetes. Wallahu a’lam bissawab.
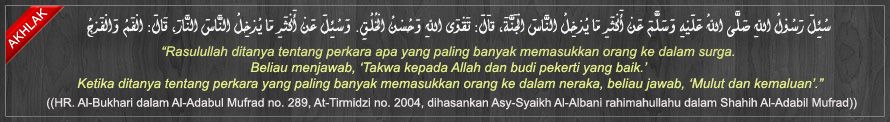
Tidak ada komentar:
Posting Komentar